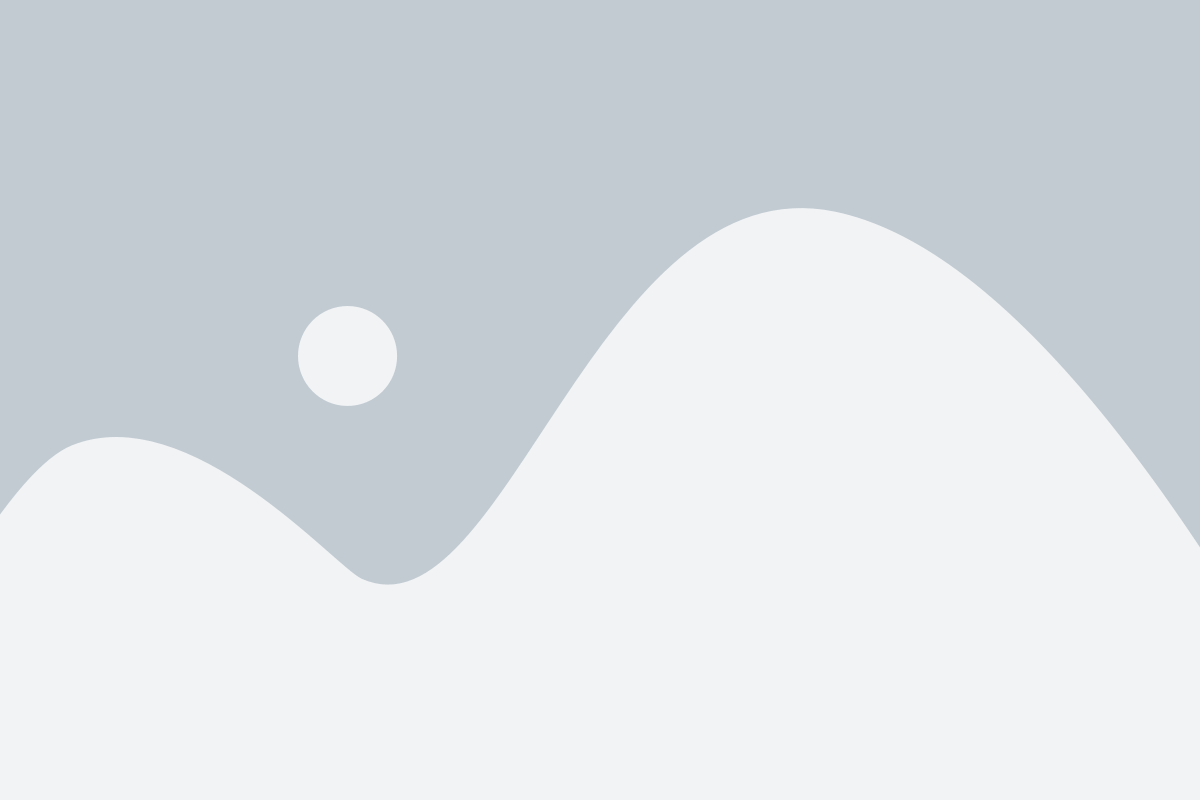Oleh A. Hajar Sanusi.
Menarik untuk disimak. Ketika Noam Chomsky (1991: 19) memulai pembahasan mengenai terosisme internasional, pakar ini mengutip cerita Santo Agustinus tentang perdebatan antara Alexander Agung dan Bajak Laut.
“Mengapa kamu berani mengacau lautan?” tanya Alexander. “Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia?” Si Bajak Laut balik bertanya. “Apakah karena aku melakukan hanya dengan perahu kecil, lalu disebut maling? Sementara kalian, karena melakukannya dengan kapal besar, lantas digelari Kaisar?” Protes Bajak Laut selanjutnya. Menurut Chomsky, kisah tersebut melukiskan secara akurat bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dan pelbagai aktor kecil di panggung terorisme internasional dewasa ini.
Cerita itu pun menjelaskan kepada kita apakah sebuah tindakan itu disebut teror atau bukan teror, tergantung pada sudut pandang masing-masing. Tidak heran kalau dalam soal ini kemudian dikenal istilah state terrorism dan non-state terrorism.
Yang pertama lazimnya merupakan instrumen kebijakan suatu rezim, atau penguasa; Sedangkan yang lainnya sebentuk perlawanan terhadap realitas ketidak-adilan poleksos, atau resistensi terhadap perlakuan represif yang ditimpakan atas seseorang atau orang banyak.
Sejak purba sampai zaman kiwari, terorisme bukanlah monopoli sebuah paham keagamaan. Apalagi dianggap khas Islam. Ideologi non-agama seperti nasionalisme, sekularisme dan atheisme pun pernah bersaham besar dalam tindakan terorisme. Misalnya, seperti Tentara Merah (Jepang), Brigade Merah (Italia) dan Macan Tamil (Srilangka) –sekedar menyebut beberapa contoh. Namun demikian mereka yang berada dalam barisan Islamo-fobia, selalu mengaitkan aneka tindakan terorisme dengan Islam. Maka dengan demikian agama yang satu ini sering dijadikan kambing hitam (scapegoat).
Simak misalnya kasus peledakan Kantor Federal di Oklahoma City, pada April 1995. Belum juga investigasi dilakukan secara seksama, Presiden AS kala itu, dengan yakin menyatakan bahwa pelakunya kelompok Islam radikal. Padahal kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah Timothy James McVeigh, seorang kulit putih dan anggota kelompok ekstrimis sayap kanan Amerika Serikat (lihat Jainuri, 2016: 137).
Sayang sekali hal itu terungkap setelah banyak Muslim di negeri Paman Sam mendapatkan perlakuan diskriminasi, bahkan perskusi dari warga non-Muslim. Yang amat menyakitkan lagi adalah, Presiden Negeri Adidaya itu tidak pernah meminta maaf kepada kaum Muslim atas tuduhan sembrono itu. Hal ini mengingatkan kita kepada penegasan Alqur’an, bahwa mereka tidak merasa, apalagi menganggap berdosa atas tindakan apapun yang mereka alamatkan kepada Kaum Beriman (QS. Ali Imran: 75).
Yang jadi pertanyaan menarik kemudian adalah, apakah gerangan faktor penyebab timbulnya terorisme itu?
Tidak dapat disangkal bahwa sebuah peristiwa sejarah terjadi, bukan sekedar lantaran beroperasinya mekanisme “tantangan” dan “jawaban” (meminjam teori Arnold J. Toynbee) semata. Melainkan juga, disebabkan oleh banyak faktor yang bekerja baik secara sendiri-sendiri, maupun sinergitas semua faktor. Dalam hal ini tindakan terorisme bukan suatu pengecualian.
Menurut banyak pakar, terorisme muncul disebabkan antara lain: Munculnya ideologi tafkiriyah. Yakni, memandang paham yang berlainan kafir, sebagai akibat dari interpretasi (tafsiran) secara eksklusif terhadap nash suci Alquran dan Hadis (kalau pelakunya seorang Muslim); Adanya ketidak-adilan pada ranah poleksos yang sangat kasat mata; Perasaan pesimis menghadapi masa depan yang tidak menentu; Timbulnya krisis kepercayaan; Dan, ketidak-berdayaan dalam memecahkan problem kehidupan.
Kalau begitu sama dong dengan keterangan sebab-sebab kelahiran radikalisme. Ya, memang antara keduanya beririsan. Meskipun harus segera ditegaskan, bahwa tidak semua radikalisme berujung pada terorisme.
Radikalisme secara leksikal radikal berasal dari kata “radix,” yang berarti akar, dasar, basis, atau fundamen; Dalam pengertian biologis-botani, radikal bermakna bagian tumbuhan yang menyerap sumber hidup; Secara filsafati, radikal adalah kecendetungan filosofis tahun 60-an sebagai lawan filsafat analitis akademik. Atau penerjemahan dan penafsiran radikal; Dari perspektif politik, radikal merupakan pemikiran dan gerakan alternatif. Pernah menjadi ciri gerakan (ekstrem) kiri, atau new left (walaupun belum tentu komunis); Adapun menurut psikologi, radikal berarti pandangan atau usulan perubahan mendasar, atau fundamental.
Berdasarkan penilaian Prof. Soetarjo (2011), radikalisme itu mengandung nilai plus-minus sekaligus. Sejauh berada pada pemikiran untuk diperdebatkan, atau adu argumentasi, radikal itu mengandung nilai positif. Bahkan, bukankah kemajuan ilmu pengetahuan itu disebabkan oleh radikalisme dalam berpikir? Adapun minusnya adalah sebagaimana dimaknai orang akhir-akhir ini. Misalnya, radikalisme adalah gerakan nyata (aksi), bersifat instan (segera) dan intoleran, serta tidak ada alternatif. Bahkan, kalau perlu dengan kekerasan.
Masalah radikalisme sejatinya dapat dicegah. Kalau ada kerjasama semua elemen masyarakat untuk meminimalisir –kalau bukan mengeleminir– pelbagai faktor tadi. Malahan kita berharap mereka yang punya kedudukan strategis, bertanggungjawab untuk membangun sistem poleksos yang berkeadilan sesuai amanah konstitusional. Yang penting radikalisme tidak dilawan dengan radikalisme lagi. Jika itu yang terjadi, maka benturan antar anak bangsa tidak mungkin dapat dielakkan.
Menurut saya beberapa hal berikut ini mungkin dapat dijadikan strategi penanganan radikalisme: Pertama, mere-edukasi kaum radikalis untuk mengubah mindset dan paham keagamaan mereka; Kedua, membuka dialog konstruktif dalam usaha memperluas wawasan. Dalam dialog diharapkan akan tercipta kondisi kejiwaan bahwa para peserta sederajat. Mereka tidak merasa sebagai tertuduh; Ketiga, tidak kalah pentingnya kegiatan publikasi dan proses sosialisasi pelbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Last but not last adanya keteladan para pemimpin –formal maupun informal– dalam mengawal dan mematahi aturan yang berlaku. Inklusif di dalamnya pemberian sanksi terhadap para pelanggar hukum tanpa diskriminatif. Dengan kata lain adanya penegakan hukum tanpa membedakan mana sang Kaisar dan mana si Bajak laut, sebagaimana dalam kisah Santo Agustinus pada awal tulisan ini. Wallahu A`lam.
Bandung, 03-10-2021.