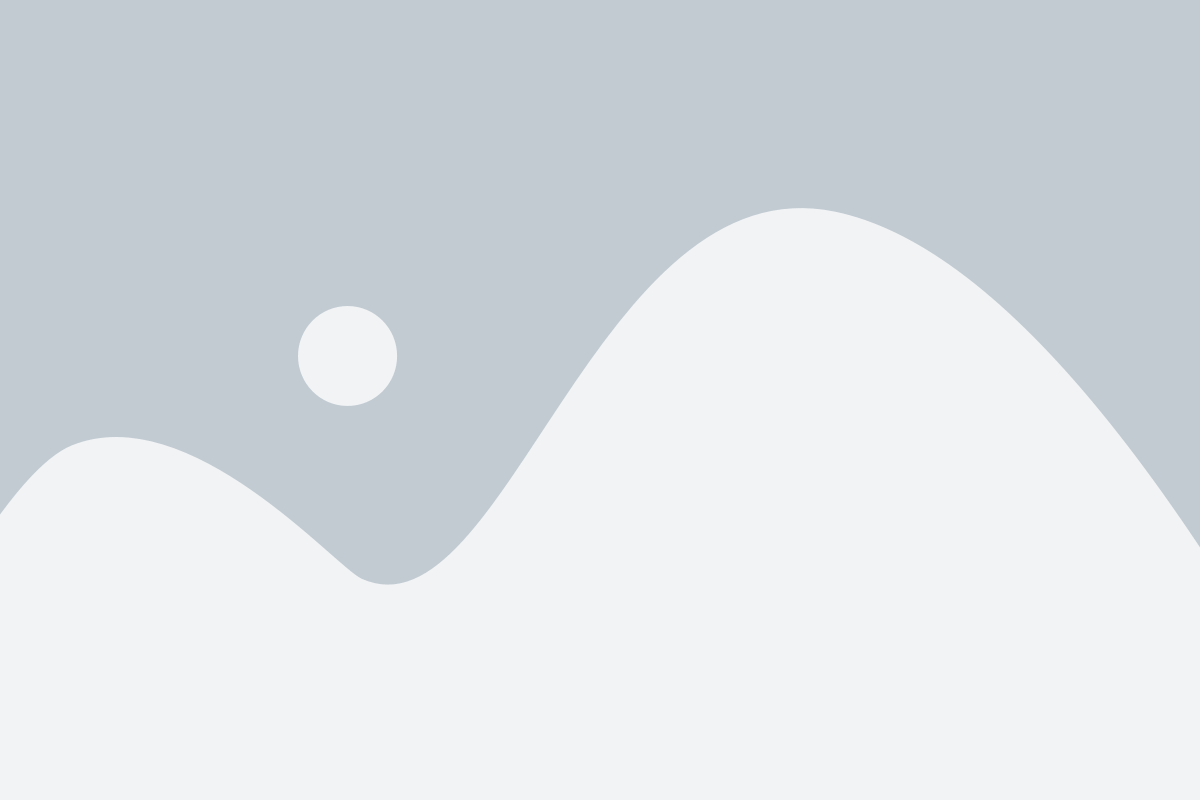Oleh A. Hajar Sanusi.
Pada awal 1980-an seorang dosen dapat beasiswa Fullbright untuk studi lanjut di Iowa State University, Buffalo (AS). Ketika diperkenalkan untuk pertama kali oleh Profesornya, yang notabene Ketua Prodi-nya juga, ia disebut sebagai mahasiswa yang “fully bright.” Maka sejak saat itu konsep diri positifnya terbentuk. Bahwa, ia adalah orang cerdas. Terlebih lagi hampir setiap hari teman sekelasnya pun memanggil ia profesor (Jabatan akademis tertinggi–bukan gelar– di PT). Berikut ini adalah pengakuannya: “Tiba-tiba saja, saya yang lulus biasa-biasa di Indonesia mendapat penghargaan yang luar biasa. Citra diri sudah terbentuk. Saya berniat mempertahankan citra diri ini. Saya cerdas, karena itu saya harus berhasil. Saya betul-betul berhasil. Konsep diri saya terbentuk karena pujian orang lain” (Rakhmat, 2008: 101).
Dua tahun kemudian ia lulus sebagai Master of Science (M.Sc.), dengan yudicium magna cum laude. Karena mendapat “perfect 4.0 grade point average,” maka kemudian ia terpilih menjadi anggota Phi Kappa Phi dan Sigma Delta Chi (Rakhmat, 2003: VI). Perlu dicatat juga keraguan dirinya: “Sampai sekarang saya masih ragu, apakah keberhasilan itu timbul karena kecerdasan saya, atau karena pujian orang lain terhadap saya” (Rakhmat, 2008: 101).
Terlepas mana yang benar dari dua kemungkinan itu, tetapi realitas membuktikan bahwa pujian orang lain yang punya kedudukan penting (significant others) ternyata memberikan pengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang. Tidak heran kalau dalam teori pendidikan mutakhir, ihwal pemberian julukan itu (labeling) dianggap signifikan untuk membangkitkan citra diri (self image) peserta didik. Penjulukan, baik positif maupun negatif, memang bersaham sangat dominan, kalau tidak dikatakan determinan, terhadap pembentukan citra diri seseorang.
Dalam psikologi sosial, citra diri (self image) merupakan salah satu dari dua komponen konsep diri. Satunya lagi adalah harga diri (self esteem). Yang pertama dikenal sebagai komponen kognitif. Sedangkan yang lainnya dinamai komponen afektif. Lazimnya, citra diri terbentuk karena label (julukan) yang disematkan pihak eksternal. Dan, lazimnya label positif melahirkan citra diri yang positif pula. Yang pada gilirannya nanti akan mewujud menjadi sebuah nurbuat yang dipenuhi dirinya sendiri (self fulfilling prophesy). Sedangkan julukan negatif, belum tentu membentuk citra diri negatif. Yang demikian itu sangat bergantung kepada komponen afektif dari konsep diri seseorang. Julukan “bodoh” belum tentu menjadikan orang itu benar-benar bodoh. Siapa tahu yang bersangkutan kemudian berusaha keras untuk mengubah citra dirinya menjadi orang pandai (ingat komponen afektif).
Penjelasan ini bermanfaat untuk mendeteksi bagaimana komponen afektif konsep diri bangsa beroperasi, ketika misalnya, ada pihak Liyan memberikan label tertentu. Misalnya, julukan bodoh, malas, khianat, pendendam, dan julukan negatif lainnya. Begitu pula bagaimana reaksi kita, ketika membaca prediksi “pakar luar” tentang masa depan universitas kita? Apakah kita mengamini secara membuta, menolak mentah-mentah, atau mengaca diri kemudian mengubah diri jadi lebih baik? Sikap yang disebut terakhir, hemat saya, lebih elegant, tidak kekanak-kanakan dan punya marwah.
Saya tidak merisaukan akademisi banyak berkiprah di ranah politik. Walaupun idealnya kaum intelektual mengambil posisi di “luar pagar,” gar tidak kelu tatkala harus menyampaikan kritik. Namun demikian, menurut Edward Shils (lihat Cendekiawan dan Politik, 1984: 236), di negara baru dan berkembang, kaum intelektual justru sangat diperlukan untuk mengelola sebuah negara. Tentu saja dengan syarat mereka tidak melacurkan intelektualisme. Atau, tidak melupakan amanat penderitaan rakyat yang di-atasnama-kannya. Dan, terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan nuraninya, seorang intelektual harus berani berkata: Tidak !! “Don’t say yes when you want to say no,” kata Herbert Fensterheim. Jika tidak demikian halnya, maka ia dianggap telah berkhianat kepada status akademikus yang disandangnya (simak karya Julien Benda, “The Betrayal of the Intellectuals”).
Elok pula kalau tidak mencaci maki mereka, dari tempat kita sekarang. Bukankah akademisi yang kini jadi sasaran kritik itu, dahulu “satu perahu” dengan kita? Ketika sama-sama tuna-kuasa, mereka pun punya pikiran kritis? Apa bisa menjamin, bahwa kita akan tetap istiqamah kalau kemudian berada di lingkar kekuasaan seperti mereka? Syukur kalau begitu. Akan tetapi terlalu sering jenis “kursi” mengubah perilaku seseorang.
Mungkin akan lebih bermanfaat kalau tugas kerisalahan yang disebut Amar Makruf Nahy Munkar (AM-NM) tetap kita jalankan dengan penuh hikmah dan mau`izhah hasanah. Bahkan, sesekali boleh juga kita gunakan mekanisme “wa jadil hum billati hiya ahsan” (QS. al-Nahl: 125).
Kembali ke masalah pentingnya “label” dalam pembentukan citra diri. Tidak heran kalau Alqur’an menjuluki kaum beriman dengan label-label positif. Simak misalnya (terjemahan) ayat berikut: “Kalian (wahai kaum Muslim) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia …” (QS. Ali Imran: 110). Atau, “Dan janganlah kamu merasa lemah, jangan pula bersedih hati. Sebab kalian adalah manusia paling tinggi derajatnya, kalau kalian orang beriman” (QS. Ali Imran: 139).
Bayangkan. Betapa tinggi apresiasi dan pujian Alqur’an terhadap kaum Muslim. “Kuntum khayra ummah” (Kalian adalah sebaik-baik umat); atau, “wa antum al-a`lawn” (Dan kalian adalah manusia yang derajatnya paling tinggi). Padahal pada saat yang sama kondisi kaum Muslim sedang lemah; Baru saja bangkit dari “kekalahan” akibat indisipliner sebagian prajurit dalam perang Uhud. Demikian pula pujian dalam Hadis Rasulullah Saw. Simak ucapan Nabi tatkala perang Ahzab. Dalam kondisi umat sangat lelah karena lapar dan kurang tidur beliau mengatakan, bahwa umatnya kelak akan menjadikan Yaman, istana merah (Romawi) dan istana putih (Persia) berada di bawah telapak mereka. Tak ayal ucapan beliau itu ditertawakan kaum munafik, karena melihat keadaan kaum Muslim begitu lemah.
Akan tetapi sejarah membuktikan, tidak lebih dari satu abad setelah beliau wafat, umatnya telah berhasil menguasai separuh dunia. Tidak kecuali imperium Yaman, Romawi dan Persia.
Apa dampak positif bagi kepribadian, ketika Alqur’an dan Hadis Nabi memberikan julukan positif dan arah prospektif itu? Yang demikian itu, menurut saya, Islam sedang membentuk citra diri positif kaum Muslim. Selaras dengan teori moderen, Islam saat itu (sejatinya sampai sekarang) sedang berusaha membangkitkan “kebanggaan kultural” (cultural pride). Sama halnya dengan yang dilakukan para pemimpin dunia dalam membangun “harga diri” bangsanya.
Perlu dicatat bahwa kaum Muslim pada masa kenabian, tidaklah sepi dari julukan buruk, kritikan, bahkan hujatan yang dilancarkan oleh kaum kuffar. Bahkan, sangat menyakitkan. Namun demikian semua itu mereka jawab dengan membentuk citra diri positif, seraya meningkatkan kesabaran dan ketakwaan (lihat QS. Ali Imran: 187). Dengan kata lain mereka tidak mengamini, atau membantah terhadap segala kritik. Melainkan dengan karya nyata mereka berupaya membuktikan bahwa dirinya ” khayra ummah” dan “al-a`lawn.”
Untuk membentuk citra diri positif, seyogianya kaum Muslim tidak perlu menunggu apresiasi dari pihak Liyan, atau dari significant others –seperti halnya pengalaman mahasiswa yang dijuluki “fully bright” oleh Profesor-nya di Iowa State University itu. Cukup dengan menghayati “julukan” yang diberikan Allah Swt dalam firman-Nya, insya Allah kita bisa bangkit dan sukses. “You don’t think what you are, you are what you think,” kata orang bijak. Wallahu A’lam.
Bandung, 01-10-2021.