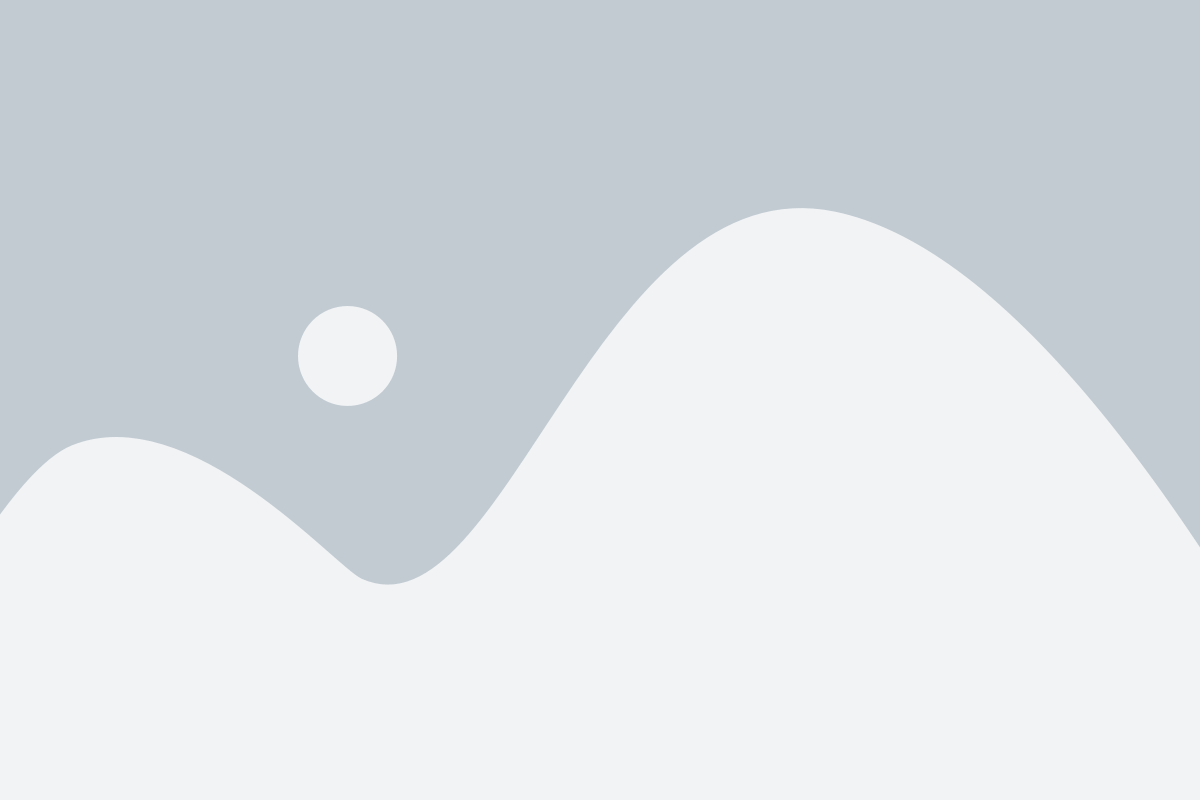Oleh A. Hajar Sanusi
Konon. Sekali waktu sejumlah orang sedang membangun masjid. Si Bahlul yang berkunjung ke tempat itu menanyakan tentang motivasi mereka dalam kegiatan tersebut. Mereka menjawab, tiada niat lain kecuali mencari ridha Allah. Kini malam tiba. Si Bahlul ingin menguji keikhlasan mereka dengan cara memasang papan di pintu masjid. Plang itu bertuliskan: “Masjid Bahlul.” Tatkala pagi harinya mereka membaca tulisan itu, keruan saja terkejut dan kesal. Mereka segera mencari, menangkap lalu memukuli si Bahlul secara beramai-ramai. “Kamu telah mencuri kelelahan orang. Kami membangun, kamu yang punya nama. Enak saja.” Demikian mereka menumpahkan kemarahan. Kini si Bahlul balik bertanya: ” Bukankah waktu kemarin ketika aku tanya, kalian menjawab semata-mata karena Allah? Jika demikian halnya maka hematku, Allah Swt pasti akan memberikan pahala kepada kalian. Kendatipun nama yang lekat pada masjid itu nama orang lain” (baca: al-`Adl al-Ilahy, 1405 H: 348).
Tentu saja validitas cerita di atas sulit diverifikasi. Namun demikian pesan moralnya sangat jelas: “Segala amal harus dialasi niat ikhkas. Sedangkan ikhlas adalah perbuatan hati. Bukan dalam ucapan. Sebab ikhlas yang diucapkan kerap kali mengandung ketidak-jujuran.” Tidak kecuali dalam hal membangun rumah ibadah.
Maka tidak heran kalau kemudian Alqur’an memilah masjid ke dalam dua kategori. Lebih mudahnya kita sebut saja: Masjid Taqwa (masjidun ussisa `ala al-taqwa) dan Masjid Dhirar.
Masjid Taqwa dibangun secara iikhlas, untuk kepentingan bermunajat (berdialog) dengan Sang Khaliq, seraya berusaha mensucikan diri ( simak QS. al-Tawbah: 108-109). Sementara Masjid Dhirar didirikan oleh orang munafik (hipokrit) dengan motivasi aneka ragam. Seperti untuk menimbulkan bencana atas Kaum Mukmin, melahirkan perpecahan internal Umat, atau berkolaborasi dengan pihak Liyan untuk memerangi Islam. Singkat kata, masjid dhirar tidak dimaksudkan untuk meraih mardhatillah.
Oleh karena itu via wahyu, Allah Swt memberitahu nabi-Nya. Maka Rasulullah Saw bersama sahabat segera menghancurkan masjid tersebut –masjid yang dibangun kaum munafik dari Bani Salim, berkolaborasi dengan Kaum Nashrani Syria, dibawah kepemimpinan Abu Amir al-Rahib (lihat Fath al-Qadir, II: 404-405).
Menyimak kejadian tersebut, kita pun mesti paham makna masjid dhirar. Atau, katakanlah: Sindrom masjid dhirar.
Sebab tidak sedikit di negeri ini masjid baru muncul, lantaran para pendiri tidak puas dengan paham dan praktik keagamaan yang dilaksanakan di masjid lama. Padahal jelas fenomena demikian dapat merobek persatuan Umat, yang sejatinya mesti dipelihara.
Selanjutnya seperti diketahui, seluruh bumi adalah suci bagi Rasulullah Saw untuk difungsikan sebagai tempat shalat. Meskipun demikian realitas menunjukkan, bahwa beliau mendirikan bangunan masjid begitu tiba di Quba, dalam rangkaian perjalanan hijrahnya.
Hal itu mengisyaratkan bahwa masjid dalam bentuk sebuah bangunan, memiliki nilai amat strategis bagi Kaum Muslim.
Melalui ekskursi sejarah masjid era kenabian, tidak sekedar berfungsi sebagai tempat shalat semata. Melainkan lebih dari itu. Misalnya, beliau memanfaatkan masjid sebagai pusat pengajaran, latihan kemiliteran, merawat korban luka perang, menjalankan politik diplomasi, menerima duta asing, memberikan advokasi buat kaum marginal, menyelesaikan konflik intra dan antarkabilah, dlsb., dlsb (lihat Gazalba, 1983: 126-137).
Singkatnya, masjid pada saat itu –tentu hari ini pun idealnya demikian– mempunyai multifungsi. Tidak terlalu mrngherankan. Sebab, pengertian masjid yang paling otentik adalah “tempat sujud.”
Kata sujud, sependek yang saya pahami, mengandung arti antara lain patuh, taat, tunduk penuh hormat dan takzim. Dalam pengertian ekstensif seperti itulah Alqur’an memaknai kata sujud.
Sekali waktu Alqur’an menggunakan kata itu untuk menjelaskan sikap hormat kepada, dan pengakuan atas kelebihan yang dimiliki pihak lain. Misalnya, sujudnya para Malaikat kepada Adam as (simak QS. al-Baqarah: 34); Di tempat lain Alqur’an menggunajan kata sujud, untuk menjelaskan kesadaran dan pengakuan akan kebenaran yang dibawa pihak lain. Contohnya adalah konversi para mantan penyihir Fir`aun setelah menyaksikan kebenaran risalah yang dibawa Musa as (lihat QS. Thaha: 70); Kata sujud itu pun berarti mengikuti dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt (baca: Hukum Takwini). Dalam konteks ini simaklah pernyataan Alqur’an tentang sujudnya bintang dan pepohonan kepada Sang Maha Pencipta (baca QS. al-Rahman: 6).
Bertolak dari paparan di atas menjadi jelas, bahwa masjid tidak sekedar tempat sujud dalam arti sempit (baca: Shalat). Melainkan juga sebagai wahana segala aktifitas Muslim (ritual, intelektual, sosial, politik, dan entah apa lagi namanya), sebagai ungkapan ketundukan mereka kepada Sang Pencipta (Khaliq). Pengertian tersebut meniscayakan para penyelenggara masjid memilki sejumlah kualifikasi: qua intelektual (faqahah), qua moral (`adalah), dan qua manajerial (kifa’ah). Tanpa semua itu, masjid akan “berjalan di tempat” (kalau tidak mau dikatan set back).
Maka dari itu, mengenai arsitektural yang menawan, “bright lights” dalam pencahayaan, serta asesoris ultra-mewah lainnya, bukanlah hal utama.
Yang penting dipikirkan para stakesholder adalah, bagaimana menjadikan masjid di masa depan sebagai Pusat Kegiatan Islam (Islamic centre). Wallahu A`lam.
Bandung, 14-09-2021.